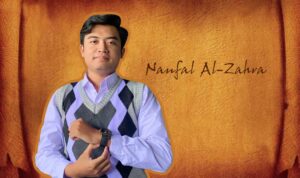RADAR TASIKMALAYA – Di tengah derasnya perubahan dunia, perguruan tinggi dituntut tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan di balik gedung megah, teknologi mutakhir, dan sederet gelar akademik yakni kurikulum.
Kurikulum sejatinya adalah jantung kehidupan akademik. Ia bukan sekadar daftar mata kuliah, melainkan arah dan nafas yang menentukan kualitas sebuah universitas. Ketika kurikulum kuat dan relevan, perguruan tinggi memiliki arah yang jelas, ketika kurikulum lemah, seluruh sistem akademik akan kehilangan pijakan.
Sejak lama, para ahli menegaskan bahwa kurikulum adalah jantung institusi pendidikan. Ralph Tyler merumuskan empat pertanyaan mendasar yakni tentang tujuan, pengalaman belajar, organisasi pengalaman, dan evaluasi hasil, yang hingga kini menjadi fondasi desain pendidikan modern.
Hilda Taba memperluas gagasan itu dengan pendekatan grassroots, menekankan bahwa kurikulum seharusnya tumbuh dari pengalaman para pendidik di lapangan, bukan semata hasil kebijakan struktural.
Peter Oliva melihat kurikulum sebagai proses dinamis yang menghubungkan teori dan praktik, sedangkan Murray Print menekankan perannya sebagai instrumen perubahan sosial yang tak terpisah dari konteks budaya dan ekonomi.
Sementara itu, Brady menegaskan perlunya keseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan nyata agar kurikulum tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi pedoman hidup yang menuntun arah akademik sebuah perguruan tinggi.
Kurikulum adalah cermin visi dan misi perguruan tinggi. Dari sana, kita dapat menilai sejauh mana lembaga pendidikan tinggi memahami tantangan zaman dan berani menjawabnya. Kurikulum yang baik tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk bekerja, tetapi juga untuk berpikir, berempati, dan berkontribusi. Sayangnya, tidak sedikit kampus yang memperlakukan kurikulum sebagai dokumen administratif semata.
Ia disusun hanya untuk memenuhi syarat akreditasi, bukan sebagai strategi akademik jangka panjang. Padahal, di balik sebuah kurikulum yang hidup, terdapat filosofi, arah kebijakan, dan nilai-nilai yang akan membentuk karakter lulusan.
Dalam konteks global, kurikulum berperan sebagai kompas intelektual yang menuntun perguruan tinggi agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dunia kerja kini berubah sangat cepat, pekerjaan lama menghilang, sementara profesi baru bermunculan setiap tahun.
Dalam situasi seperti ini, universitas tidak cukup hanya mengajarkan teori. Mereka harus mengajarkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan adaptif. Semua itu dimulai dari kurikulum yang dirancang dengan visi ke depan. Kurikulum yang baik tidak berdiri di menara gading. Ia harus menyapa dunia nyata. Artinya, setiap rancangan pembelajaran perlu dikaitkan dengan kebutuhan industri, masyarakat, dan perkembangan sosial.
Perguruan tinggi perlu menggandeng mitra luar kampus: dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, hingga masyarakat. Kolaborasi inilah yang membuat kurikulum menjadi dinamis dan kontekstual.
Di banyak universitas maju, pembaruan kurikulum menjadi agenda rutin, bukan proyek musiman. Setiap beberapa tahun, dilakukan curriculum review, melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Tujuannya sederhana yaitu memastikan apa yang diajarkan di ruang kuliah benar-benar bermanfaat di lapangan kerja dan kehidupan sosial.
Pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang kini banyak diadopsi kampus di Indonesia sebenarnya lahir dari semangat yang sama yakni menempatkan capaian pembelajaran sebagai orientasi utama. Artinya, mahasiswa tidak lagi sekadar “menyelesaikan mata kuliah”, tetapi mencapai kompetensi yang jelas, terukur, dan relevan.
Kampus tidak lagi berfokus pada seberapa banyak materi diberikan, tetapi pada seberapa dalam mahasiswa memahami dan mampu menerapkannya. Namun, kurikulum tidak akan bermakna tanpa pelaku yang menjalankannya dengan sungguh-sungguh.
Dosen menjadi ujung tombak penerjemahan kurikulum di lapangan. Mereka bukan sekadar pengajar, tetapi perancang pengalaman belajar. Ketika dosen memahami filosofi kurikulum, proses belajar menjadi hidup, mahasiswa diajak berpikir, berdiskusi, memecahkan masalah, bukan sekadar mencatat dan menghafal. Sebaliknya, mahasiswa juga tidak boleh pasif.
Kurikulum yang berbasis pada mahasiswa menuntut peran aktif mereka sebagai pembelajar mandiri. Mahasiswa harus berani bertanya, meneliti, bahkan mengkritisi materi. Dalam dinamika inilah, kurikulum menjadi ruang dialog intelektual, bukan sekadar sistem pengajaran satu arah.
Selain sebagai instrumen akademik, kurikulum juga merupakan bentuk akuntabilitas publik. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya diajarkan di kampus? Kompetensi apa yang diperoleh mahasiswa? Bagaimana kurikulum itu menjawab tantangan sosial di sekitarnya? Di sinilah pentingnya evaluasi kurikulum yang transparan. Perguruan tinggi kini diharapkan menerapkan sistem penjaminan mutu dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
Artinya, setiap rancangan kurikulum harus melewati proses uji kualitas, dimonitor secara berkala, dan terus diperbaiki. Dengan cara itu, universitas bisa memastikan kurikulumnya bukan sekadar dokumen di rak, tetapi sistem hidup yang terus berevolusi.
Lebih jauh, kurikulum juga menjadi cermin identitas universitas. Kampus dengan akar riset yang kuat akan menonjolkan metode ilmiah dan penelitian. Perguruan tinggi vokasi akan menekankan praktik dan keahlian kerja.
Dan kampus yang berbasis nilai-nilai lokal akan menjadikan kearifan daerah sebagai kekuatan khasnya. Dalam konteks Indonesia, kurikulum yang baik seharusnya tidak meniru mentah-mentah model luar negeri, melainkan menyesuaikannya dengan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat.
Pendidikan tinggi bukan pabrik gelar, melainkan laboratorium nilai dan kebijaksanaan. Kurikulum harus menjadi jembatan antara ilmu dan kemanusiaan.
Kurikulum masa depan harus fleksibel, terbuka, dan humanis. Fleksibel agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan cepat dunia digital. Terbuka agar lintas disiplin ilmu dapat saling berkolaborasi, karena masalah dunia nyata tidak pernah berdiri sendiri. Dan humanis agar pendidikan tidak kehilangan ruhnya yakni memanusiakan manusia.
Universitas yang berani melakukan inovasi kurikulum, mengintegrasikan riset, pengabdian, dan teknologi digital dalam pembelajaran akan menjadi pelopor transformasi pendidikan nasional. Dari kampus seperti inilah lahir generasi yang tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi menciptakan perubahan. Menjaga kualitas kurikulum berarti menjaga marwah perguruan tinggi. Sebab di balik setiap mata kuliah, capaian pembelajaran, dan aktivitas akademik, tersimpan tanggung jawab luhur untuk mencerdaskan bangsa.
Perguruan tinggi yang memahami hakikat itu akan selalu berbenah dengan tenang dan bijak, tidak karena tuntutan birokrasi, tetapi karena kesadaran bahwa masa depan pendidikan bukan dimulai dari ruang seminar, melainkan dari ruang kurikulum yang senantiasa diperbarui dengan hati dan pikiran yang jernih. (Bayu Adi Laksono)
Penulis merupakan Dosen Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi (Unsil), Mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya