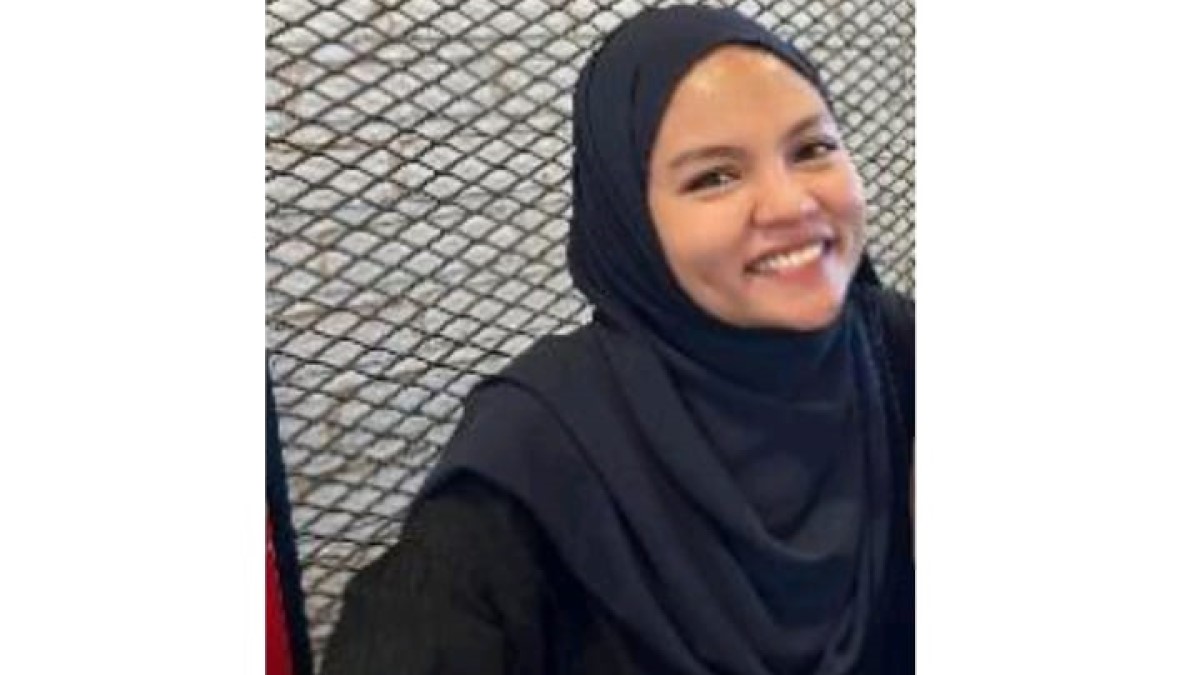RADAR TASIKMALAYA – Di balik senyum mahasiswa yang berlalu-lalang di koridor kampus, terkadang tersembunyi cerita yang jarang terdengar. Ada yang datang ke kelas dengan perut kosong karena masalah ekonomi, tapi tetap berusaha terlihat biasa saja.
Ada yang aktif di organisasi, namun hidupnya tertekan oleh senioritas yang menindas. Ada pula yang tampak ceria di antara teman-temannya, padahal lama kehilangan arah dan semangat hidup. Tidak semua luka terlihat secara kasat mata, tidak semua tangis terdengar oleh telinga, dan tidak semua permintaan bantuan mampu menembus tembok budaya akademik yang dingin.
Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap 40 detik, satu individu di dunia ini mengakhiri hidupnya melalui bunuh diri. Sementara itu, Unicef melaporkan bahwa 29 persen generasi muda Indonesia sering mengalami depresi, dengan sebagian dari mereka bahkan mempertimbangkan bunuh diri.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat bahwa banyak kasus bunuh diri terjadi pada usia 15-24 tahun, rentang usia yang sebagian besar diisi oleh mahasiswa. Hal ini menegaskan bahwa kampus bukan sekadar ruang pembelajaran, melainkan juga arena di mana banyak generasi muda berjuang dalam diam melawan tekanan mental yang berat.
Angka-angka ini bukanlah sekadar statistik abstrak, ini merupakan alarm darurat yang menunjukkan kondisi kesehatan mental yang genting, termasuk di lingkungan akademik.
Selama ini kita diajarkan bahwa kampus adalah ruang pengetahuan dan kemanusiaan. Nyatanya, kampus juga bisa menjadi tempat berkembangnya kekerasan psikis yang dianggap wajar. Bentuknya bisa halus, berupa penghinaan dibungkus candaan, intimidasi dikemas sebagai pembinaan, kritik berubah menjadi serangan pribadi, atau senioritas dijadikan tradisi yang tak terbantahkan.
Ironisnya, perilaku semacam ini dianggap normal dan sering diwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus kekerasan psikis terjadi di Indonesia khususnya dilingkungan kampus. Pada 15 Oktober 2025, publik dikejutkan oleh kasus bunuh diri mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugerah Saputra, yang diduga mengalami bullying.
Dua hari kemudian, mahasiswa UIN Raden Mas Said, Hanna Putri Nugrahani, mengakhiri hidupnya akibat tekanan psikologis yang berat. Tragedi-tragedi ini mengindikasikan bahwa isu kesehatan mental mahasiswa bukanlah masalah individu semata, melainkan persoalan struktural yang mendalam.
Fenomena ini dikenal sebagai toxic academic culture, budaya akademik yang secara sistematis melanggengkan kekerasan psikis. Dampaknya tidak selalu fisik tetapi serius, dapat meruntuhkan harga diri, menghancurkan kepercayaan diri, dan mematikan semangat hidup.
Pelaku sering merasa benar karena menganggap punya legitimasi moral, baik apakah mereka senior, pengurus organisasi, dosen, atau pejabat kampus. Kekerasan psikis dibungkus sebagai pelatihan mental, ujian loyalitas, atau metode pembentukan karakter.
Padahal, membangun karakter tidak perlu menyakiti orang lain.
Relasi kuasa juga memperburuk situasi. Mahasiswa junior takut bersuara karena khawatir dikucilkan. Dalam bimbingan akademik, mereka enggan melapor karena nasib studi bergantung pada dosen pembimbing.
Dalam program profesi seperti kedokteran, farmasi, atau keperawatan, tekanan psikologis dilembagakan atas nama hierarki keilmuan. Sedikit terlambat, dimarahi. Mengkritik, dianggap tidak loyal. Melapor, dianggap durhaka. Pelan-pelan, sistem akademik menghancurkan keberanian mahasiswa mempertahankan martabatnya. Yang lebih menyedihkan, terkadang kampus sering gagal menjadi pelindung. Saat korban melapor, pertanyaan pertama yang muncul, “Apa buktinya?” Seolah luka batin harus difoto atau direkam agar dianggap nyata.
Akibatnya, korban merasa sendirian. Padahal, penelitian psikologi klinis Universitas Indonesia menunjukkan kekerasan psikis memiliki dampak jangka panjang setara kekerasan fisik, yaitu trauma, kecemasan kronis, gangguan tidur, penurunan fungsi kognitif, hingga pikiran bunuh diri.
Krisis kesehatan mental di kampus tidak bisa diatasi dengan seminar setahun sekali atau unggahan awareness di media sosial. Kampus harus bertindak nyata. Pertama, sistem konseling perlu diperbaiki secara serius. Banyak pusat layanan psikologi hanya formalitas tanpa tenaga profesional.
Konseling harus independen dan berpihak pada mahasiswa. Kedua, Satgas PPKPT harus diperkuat sebagai garda terdepan penanganan kekerasan, dengan dukungan penuh untuk setiap kasus, termasuk pendanaan, pelatihan, dan perlindungan bagi korban. Ketiga, budaya akademik harus dibersihkan dari kekerasan verbal dan senioritas yang toxic. Tidak ada ilmu yang layak diajarkan dengan penghinaan.
Namun, perbaikan struktural saja tidak cukup. Empati harus kembali hidup di kampus. Kita gagal sebagai masyarakat jika masih menstigma mahasiswa yang depresi sebagai “kurang iman” atau “kurang kuat”. Kesehatan mental bukan kelemahan, dan meminta bantuan bukan aib.
Akhirnya, kampus harus menjadi ruang yang memanusiakan manusia. Tempat ilmu membebaskan, bukan menindas. Tempat dialog berjalan dengan saling menghormati, bukan rasa takut. Tempat karakter dibangun dengan integritas, bukan kekerasan. Tempat setiap mahasiswa merasa aman untuk belajar, bertanya, berproses, bahkan gagal.
Jika hari ini kita melihat seorang mahasiswa tersenyum di koridor, jangan cepat berasumsi ia baik-baik saja. Bisa jadi ia sedang menahan runtuh. Bisa jadi kemarin ia berpikir mengakhiri hidupnya. Atau mungkin ia hanya menunggu seseorang yang benar-benar peduli dan bertanya, “Kamu sungguh baik-baik saja?” Sebelum kita kehilangan lebih banyak Timothy lainnya, kita harus memilih, diam dan menjadi bagian dari masalah, atau bersuara dan menjadi bagian dari perubahan. (Sandra Leoni P Yakub)
Penulis merupakan Dosen FISIP dan Anggota Satgas PPKPT Universitas Siliwangi