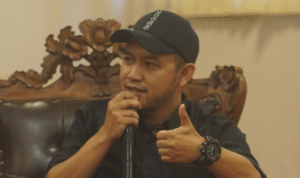RADAR TASIKMALAYA – Setiap kali isu darurat militer muncul, publik hampir selalu dibuat resah. Dari segi hukum, kebijakan ini sah karena memang diatur dalam konstitusi di mana negara diberi kewenangan mengambil langkah luar biasa demi menjaga keutuhan bangsa. UUD NRI Tahun 1945 lewat Pasal 12 menegaskan Presiden berhak menyatakan keadaan bahaya, yang kemudian dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya.
Ada tiga bentuk keadaan bahaya, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang. Secara teori, darurat militer diberlakukan ketika cara-cara biasa sudah tak lagi mampu menjaga keamanan. Tetapi, legalitas tidak selalu berarti aman bagi demokrasi maupun adil dalam kehidupan masyarakat.
Sejarah Indonesia membuktikan hal itu. Pada 1957, darurat militer dipakai untuk meredam pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta pada 1958. Lalu, pada 1965, situasi serupa kembali muncul saat penumpasan G30S/PKI. Memang benar, status ini membantu negara memulihkan stabilitas. Namun jejak gelapnya juga jelas, adanya pembungkaman pers, penangkapan sewenang-wenang, oposisi yang dibungkam, hingga kekerasan yang sulit dipertanggungjawabkan.
Hal ini yang tertuang di Pasal 26 Perpu No. 23 Tahun 1959 salah satu hak Penguasa Darurat Militer adalah mengadakan tindakan-tindakan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apa pun, termasuk lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.
Bahkan Penguasa Darurat Militer berhak menyuruh menahan atau menyita semua surat-surat dan kiriman-kiriman lain yang dipercayakan kepada jawatan pos atau jawatan pengangkutan lain serta wesel-wesel dan kuitansi-kuitansi bersama jumlah uang yang disetor dan dipungut, termasuk membuka, melihat, memeriksa, menghancurkan atau mengubah isi dan membuat supaya tidak dapat dibaca lagi surat-surat atau kiriman-kiriman itu, dan banyak lagi hak lainnya yang diatur dalam Perpu No. 23 Tahun 1959 tersebut.
Kenapa darurat militer dianggap berbahaya? Pertama, karena secara langsung ia membatasi hak-hak sipil yang seharusnya dilindungi konstitusi. Dengan alasan keamanan nasional, ruang kebebasan bisa dipangkas habis-habisan.
Hak untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul bisa dikebiri. Pers bisa diseret ke dalam sensor negara, unjuk rasa bisa dipandang sebagai ancaman stabilitas, bahkan aktivitas masyarakat sehari-hari bisa diawasi ketat oleh aparat. Padahal, kebebasan sipil adalah jantung demokrasi. Tanpa itu, masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengoreksi pemerintah. Akibatnya, kebijakan yang keliru bisa terus berjalan tanpa kontrol publik.
Kedua, darurat militer hampir selalu menyeret militer masuk terlalu jauh ke ranah sipil. Tentara yang mestinya fokus menjaga pertahanan dari ancaman luar, mulai ikut mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Fungsi sipil dalam negara demokratis pun diperkecil. Bahkan ketika status darurat sudah berakhir, jejak kekuasaan militer sering masih terasa, membentuk budaya politik yang cenderung otoriter. Pengalaman panjang Orde Baru adalah contoh paling jelas di mana pengaruh militer begitu dalam sehingga membekas bahkan setelah rezim itu tumbang.
Ketiga, darurat militer membuka peluang besar terjadinya penyalahgunaan wewenang. Saat mekanisme hukum biasa ditangguhkan, aparat memiliki keleluasaan yang sangat luas. Penangkapan bisa dilakukan tanpa prosedur hukum jelas, ekspresi kritis bisa dipidana, bahkan tindakan represif bisa “dilegalkan” melalui aturan sementara. Kekuasaan absolut tanpa pengawasan hampir pasti berujung pada penyalahgunaan.
Banyak contoh di dunia menunjukkan hal serupa, keadaan darurat yang seharusnya sementara malah dipertahankan lama-lama demi mengamankan posisi penguasa. Misalnya, Mesir di bawah Presiden Hosni Mubarak menerapkan state of emergency sejak tahun 1981 setelah pembunuhan Presiden Anwar Sadat. Status ini, yang semula dimaksudkan untuk mengatasi ancaman keamanan, justru berlangsung selama hampir 30 tahun tanpa henti. Dampaknya sangat luas, kebebasan sipil terkekang, oposisi politik ditekan, dan aparat punya wewenang besar melakukan penahanan tanpa proses hukum jelas.
Contoh lain adalah Turki pasca kudeta gagal 2016. Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan memberlakukan keadaan darurat selama dua tahun. Selama periode itu, ribuan orang ditangkap, media independen dibatasi, dan kebijakan represif dilegalkan dengan dalih menjaga stabilitas. Banyak pengamat menilai, keadaan darurat tersebut menjadi pintu masuk konsolidasi kekuasaan Erdogan, yang akhirnya memperlemah demokrasi Turki.
Peringatan ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum tata negara. Jimly Asshiddiqie, misalnya, mengingatkan bahwa prinsip konstitusionalisme tidak boleh hilang meski dalam keadaan darurat. Ia menekankan bahwa keadaan luar biasa sering dijadikan alasan untuk memperluas kewenangan tanpa batas. Mahfud MD menambahkan, darurat militer memang sah, tetapi pelaksanaannya wajib tunduk pada prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan batasan waktu yang jelas. Tanpa itu, kebijakan ini berubah dari solusi menjadi masalah.
Di sinilah pentingnya prinsip trias politika dan mekanisme check and balances. Kekuasaan Presiden memang diakui konstitusi, tetapi tidak boleh berdiri sendiri. DPR harus aktif mengawasi, Mahkamah Konstitusi harus memastikan tidak ada penyimpangan, dan masyarakat sipil bersama pers berperan menjaga transparansi di lapangan. Tanpa pengawasan seperti ini, darurat militer bisa jadi pintu masuk otoritarianisme.
Karena itu, darurat militer seharusnya dipandang sebagai jalan terakhir, bukan jalan pintas. Indonesia sebenarnya punya banyak instrumen hukum lain. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menawarkan mekanisme resolusi konflik tanpa harus mengorbankan demokrasi. UU No. 34 tahun 2004 tantang TNI juga memungkinkan pengerahan militer dengan batasan jelas, tetap dalam kerangka sipil. Selama opsi-opsi ini tersedia, darurat militer sebaiknya dihindari. Sekali pintu itu dibuka, pembatasan hak sipil akan sulit dikembalikan seperti semula.
Lalu, apakah darurat militer masih relevan di era modern? Jawabannya: ya, tapi hanya dalam kondisi benar-benar ekstrem. Indonesia tentu harus siap menghadapi ancaman besar seperti terorisme, pemberontakan bersenjata, atau agresi asing. Namun kesiapan itu jangan sampai menjadikan darurat militer sebagai solusi instan untuk tiap masalah. Filipina bisa jadi pelajaran. Di Mindanao, darurat militer diberlakukan dengan alasan menghadapi kelompok bersenjata. Tapi dampaknya justru memperburuk kondisi HAM dan mengikis demokrasi. Indonesia bisa terjebak pada pola serupa jika tidak hati-hati.
Pada dasarnya, darurat militer memang sah secara hukum, tapi dampaknya bisa sangat mahal bagi demokrasi. Ia mungkin meredam krisis sesaat, tetapi berpotensi merusak fondasi kebebasan dalam jangka panjang. Maka, status ini harus ditempatkan layaknya palu pemecah kaca darurat, hanya dipakai ketika situasi benar-benar tak terkendali. Indonesia butuh negara yang kuat, tapi juga demokrasi yang sehat. Jangan sampai demi menyelamatkan bangsa, kita justru kehilangan kebebasan yang menjadi ruh kehidupan bernegara. (Sandra Leoni Prakasa Yakub)
Penulis merupakan Dosen FISIP Unsil