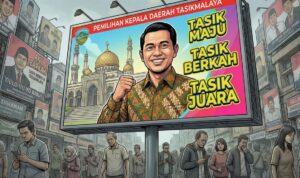RADAR TASIKMALAYA – Dunia pernah memahami kekuasaan sebagai sesuatu yang berwujud fisik wilayah yang direbut, pasukan yang disiagakan, atau kapal perang yang melintasi lautan. Namun, di abad ke-21, definisi kekuasaan berubah secepat teknologi berkembang. Kini, batas negara lebih banyak ditentukan oleh jaringan kabel optik, arus data, dan algoritma yang diam-diam mengatur ritme kehidupan sehari-hari. Di balik layar yang tampak tenang, dunia tengah bergeser menuju arena geopolitik baru: ruang digital. Pertarungan yang terjadi di dalamnya tidak menimbulkan dentuman, tetapi efeknya dapat mengguncang struktur sosial, politik, bahkan kedaulatan sebuah negara.
Colin S. Gray, seorang pemikir besar dalam kajian strategi, mengingatkan bahwa geopolitik selalu berhubungan dengan tiga unsur: ruang, kekuasaan, dan teknologi. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Jika pada era klasik ruang itu berarti daratan atau lautan, hari ini ruang itu telah bermigrasi ke dunia maya. Ruang digital menjadi ”medan” baru tempat negara-negara menguji kekuatan dan ketahanan mereka. Pertanyaannya bukan lagi siapa menguasai wilayah, tetapi siapa menguasai infrastruktur digital, jaringan data, dan mekanisme kendali atas informasi publik.
Dinamika geopolitik digital global ini semakin terasa ketika negara-negara besar saling memperebutkan dominasi teknologi. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dalam kompetisi 5G, AI, dan teknologi cloud, misalnya, menciptakan tekanan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk menentukan posisi strategis. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google, Meta, TikTok, dan Alibaba bukan hanya pemain ekonomi; mereka adalah aktor geopolitik yang mampu mempengaruhi opini publik, memetakan perilaku masyarakat, hingga memengaruhi dinamika politik domestik melalui algoritma yang tak terlihat.
Indonesia berada di tengah pusaran ini. Dengan lebih dari 210 juta pengguna internet, salah satu pasar digital terbesar di dunia, dan letak geografis yang dilintasi jalur kabel optik internasional, Indonesia menjadi wilayah strategis dalam peta persaingan digital global. Tekanan dan tarikan dari pertarungan global inilah yang pada akhirnya membentuk arah kebijakan siber nasional.
Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat pertahanan dan tata kelola digitalnya. Lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 2017 menandai perubahan besar: negara mengakui bahwa ruang siber adalah arena pertahanan, bukan sekadar domain teknis. Pembentukan BSSN diikuti penyusunan Strategi Keamanan Siber Nasional, yang menegaskan pentingnya perlindungan infrastruktur kritis, sistem pemerintahan digital, serta kewaspadaan terhadap ancaman siber lintas negara.
Selain itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 2022, sebuah tonggak penting dalam memperbaiki tata kelola data nasional. UU ini hadir bukan semata-mata karena kebutuhan domestik, tetapi sebagai respons terhadap tekanan global mengenai standar perlindungan data, risiko kebocoran informasi, dan dominasi platform asing yang menguasai data warga Indonesia. Kehadiran UU PDP sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi digital internasional.
Namun upaya Indonesia tidak berhenti di situ. Regulasi seperti UU ITE, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), hingga aturan mengenai kewajiban pembangunan Pusat Data Nasional adalah bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan teknologi pada pihak asing. Ketentuan tentang lokalisasi data, misalnya, adalah bentuk pertahanan struktural untuk memastikan bahwa data strategis warga negara tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan global.
Kebijakan-kebijakan tersebut tidak lahir dalam ruang hampa. Ia terbentuk karena tekanan persaingan digital antarnegara yang semakin intens. Setiap kebocoran data, setiap serangan terhadap sistem pemerintahan, dan setiap upaya disinformasi berbasis algoritma menjadi alarm bagi negara untuk tidak memandang ruang digital sebagai wilayah netral. Pada titik inilah analisis Colin S. Gray kembali relevan: negara harus memastikan keselarasan antara kepentingan nasional, kemampuan teknologi, dan strategi yang diterapkan. Tanpa itu, sebuah negara akan mudah terseret arus geopolitik global tanpa kemampuan mengendalikan arah pergerakannya sendiri.
Dalam konteks Indonesia, keselarasan tersebut masih terus dibangun. Pemerintah, misalnya, mulai mengembangkan diplomasi digital dengan lebih serius melalui forum ASEAN, G20, hingga keterlibatan dalam diskusi global mengenai tata kelola kecerdasan buatan. Langkah ini penting karena Indonesia tidak mungkin bertahan sendirian dalam lanskap digital yang sangat terhubung. Diplomasi digital membuka ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan tata kelola dunia maya yang lebih adil, etis, dan aman bagi negara-negara berkembang.
Namun tantangan terbesarnya adalah bagaimana menata ulang hubungan antara negara, platform digital global, dan warga negara. Algoritma yang bekerja di balik layar telah menjadi kekuatan politik baru. Mereka mengatur apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, hingga bagaimana kita membentuk opini. Jika negara tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan mengelola algoritma ini, maka kedaulatan digital hanya akan menjadi slogan tanpa substansi.
Pada akhirnya, masa depan digital Indonesia bergantung pada keberanian untuk melihat ruang siber sebagai arena strategis yang menentukan nasib bangsa. Perjuangan mempertahankan kedaulatan digital bukan perang melawan teknologi, tetapi perjuangan untuk memastikan bahwa teknologi berpihak pada kepentingan nasional dan kemanusiaan. Dunia mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi di balik layar, pertarungan sedang berlangsung. Dan Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perang senyap yang akan menentukan masa depan ini. (Rysha Nadya Permana)
Penulis merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya.