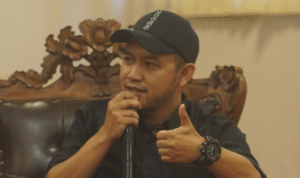RADAR TASIKMALAYA – Cara pandang sebagian besar masyarakat dunia termasuk bangsa Indonesia dalam memaknai kemajuan, modernitas, dan perbedaan nilai-nilai budaya sering kali dipengaruhi oleh narasi dominan yang bersumber dari sistem pengetahuan Barat.
Hal ini merupakan salah satu dampak kolonialisme jangka panjang. Banyak masyarakat Indonesia yang hingga saat ini memiliki mental inferiority complex. Moritz dkk (2006) mengatakan bahwa inferiority complex adalah suatu kondisi psikologis individu meliputi rasa kurang percaya diri, tidak menghargai diri sendiri, atau merasa dirinya di bawah standar, baik disadari ataupun tidak.
Dalam karyanya yang berjudul Orientalism, Edward Said (1978) menunjukkan bagaimana dunia non-Barat dikonstruksikan sebagai “the Other” atau “yang Liyan” melalui lensa eurosentris, yang akhirnya melahirkan hierarki intelektual, budaya, dan identitas. Namun, dalam kajian pascakolonial, identitas kini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk melalui sejarah, Bahasa, pengalaman, dan relasi kuasa.
Refleksi teoritis ini menjadi relevan saat saya mengikuti program pertukaran mahasiswa antar universitas di Uni Eropa bertajuk Connecting Cultures: Sustainability, Travel, Translation & Migration di Vitoria-Gasteiz, Spanyol. Program ini bukan hanya memperkenalkan teori-teori tentang bagaimana travel writing, ekoliterasi, dan migrasi bisa menjadi sarana untuk memertahankan keberlanjutan identitas budaya suatu bangsa, tetapi juga menjadi ruang reflektif yang menantang cara saya memahami identitas dan posisi saya sebagai individu.
Dalam interaksi lintas budaya tersebut, saya menyadari bahwa cara saya memandang Barat sebagai pusat kemajuan dan modernitas merupakan bagian dari konstruksi sosial yang telah tertanam sejak lama, sebuah hasil dari internalisasi narasi hegemonik yang sering kali tidak disadari.
Lahir dan besar di Tasikmalaya, sebuah kota di tatar Priangan dengan nilai religiusitas dan komunalitas yang kuat, saya, seperti banyak orang Indonesia lainnya, tumbuh dengan persepsi bahwa segala sesuatu yang datang dari Barat biasanya lebih baik karena lebih modern, saintifik, maju, dan dapat dipercaya. Pikiran ini merupakan sisa-sisa cara pandang eurocentrisme yang diwariskan sejak masa kolonial, bahwa peradaban manusia saat ini berpuncak di Eropa dan segala sesuatu di luarnya bersifat tertinggal.
Memang benar, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa banyak kemajuan dunia saat ini bersumber dari inovasi dan pemikiran yang berkembang di Eropa dan dunia Barat, dari Revolusi Industri, teknologi digital, hingga pemikiran demokrasi dan hak asasi manusia.
Dalam sistem pendidikan mereka, saya menyaksikan secara langsung bagaimana guru tidak lagi menjadi otoritas mutlak, melainkan rekan diskusi yang membuka ruang kritis bagi siswa. Namun, penghargaan terhadap guru tetap dijaga, bukan karena posisi sosialnya, tetapi karena keilmuannya, sebuah bentuk meritokrasi yang sangat menginspirasi.
Sistem meritokrasi ini telah diperjuangkan oleh banyak ilmuwan sosial Barat. Michael Young, dalam bukunya The Rise of the Meritocracy (1958), memperkenalkan konsep meritokrasi sebagai sistem di mana keberhasilan seseorang didasarkan pada kemampuan dan usaha, bukan warisan atau kekuasaan. Meski awalnya ditulis sebagai satir, ide meritokrasi diadopsi secara luas sebagai cita-cita masyarakat modern. Selain itu, karya-karya seperti Justice as Fairness (John Rawls, 1971) dan Capital in the Twenty-First Century (Thomas Piketty, 2013) juga mengkritisi ketimpangan dan mendorong keadilan sosial berbasis kompetensi individu.
Namun, apakah semua idealisme tersebut benar-benar terealisasi di Eropa? Mungkin iya, tetapi tidak seluruhnya.
Selama berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai negara, saya menyaksikan bahwa isu rasisme masih sangat kuat mengakar. Sebagai contoh, tidak hanya teman-teman non-Barat yang sering kali mengalami stereotip dan diskriminasi bernada halus, mulai dari pengabaian pendapat dalam diskusi kelompok, hingga asumsi-asumsi otomatis tentang kapasitas intelektual, namun terhadap yang sesama masyarakat Barat hal tersebut juga berlaku.
Padahal mereka adalah bagian dari komunitas akademik yang seharusnya menjunjung tinggi kesetaraan dan rasionalitas. Fenomena ini dikenal sebagai diskriminasi mikro (microaggressions), yaitu bentuk-bentuk perlakuan diskriminatif yang bersifat halus, sering kali tidak disadari pelakunya, namun berdampak besar secara psikologis dan sosial bagi yang mengalaminya. Menurut Sue dkk. (2007), microaggressions terdiri dari tiga bentuk: microassaults (serangan verbal/non-verbal eksplisit), microinsults (komentar merendahkan atau meragukan kapabilitas seseorang berdasarkan identitasnya), dan microinvalidations (menyangkal pengalaman atau identitas seseorang). Salah satu contoh yang saya temui adalah ketika mahasiswa dari Asia merasa pendapatnya lebih sering “tidak didengarkan” dalam diskusi kelas, atau justru diulang oleh peserta lain dari Eropa dan baru kemudian dianggap valid.
Lebih jauh, diskusi akademik pun kadang dikemas dalam diksi-diksi yang mempolarisasi. Misalnya, istilah “negara dunia ketiga” atau “underdeveloped” yang sering digunakan untuk menggambarkan negara-negara di Global South, membawa implikasi hierarkis dan merendahkan. Padahal, menurut Escobar (1995) dalam Encountering Development, konsep pembangunan itu sendiri lahir dari sudut pandang Barat yang mendefinisikan siapa yang “maju” dan siapa yang “tertinggal”, tanpa mempertimbangkan kompleksitas sejarah dan konteks lokal.
Kondisi ini membuat saya merenung, mungkin kita di Indonesia tidak semaju dalam pengertian teknologi dan sains, tetapi kita punya nilai-nilai sosial yang sangat kuat, yang justru sulit ditemukan di banyak tempat di Eropa. Di Tasikmalaya, gotong royong bukanlah konsep teoretis, tetapi kenyataan hidup. Kepedulian terhadap tetangga, berbagi makanan, membantu saat musibah, atau sekadar menyapa hangat di jalan, semua ini adalah bentuk dari nilai sosial yang mendalam dan terus hidup.
Dalam tradisi kita, kesuksesan tidak hanya diukur dari pencapaian pribadi, tetapi juga dari kontribusi terhadap komunitas. Ini mungkin terdengar “tradisional”, tapi dalam dunia yang semakin individualistik dan terpolarisasi, nilai-nilai ini justru menjadi semakin relevan dan dibutuhkan.
Dulu, nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, atau saling menghormati cenderung dianggap sebagai bagian dari “budaya Timur” yang terkait erat dengan batas geografis dan bangsa. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran kolektif global, kita mulai menyadari bahwa nilai-nilai tersebut bersifat universal. Mereka tidak dimiliki oleh bangsa tertentu, melainkan dapat ditemukan dalam individu-individu dari berbagai latar belakang.
Sebaliknya, kita juga harus membangun kesadaran bahwa tidak semua orang Barat itu individualistik, dan tidak semua orang Indonesia itu komunal. Ada orang Eropa yang sangat kolektif dalam cara berpikir dan bertindak, dan ada pula orang Indonesia yang sangat individualistis. Ini menggambarkan bahwa klasifikasi manusia berdasarkan bangsa dan budaya kini menjadi semakin usang dan tidak relevan.
Pendekatan seperti ini dikenal dalam kajian budaya sebagai pendekatan non-essentialist. Adrian Holliday (2010) dalam bukunya Intercultural Communication and Ideology, menyatakan bahwa kita harus meninggalkan cara berpikir esensialis, yaitu menganggap budaya sebagai sesuatu yang statis, homogen, dan bisa dikotakkan menurut bangsa. Sebaliknya, kita perlu melihat budaya sebagai proses yang dinamis dan manusia sebagai individu yang kompleks – mereka dipengaruhi oleh budaya, tapi juga memiliki kemampuan untuk memilih, menolak, dan mengubah nilai-nilai itu.
Apa pesan perdamaiannya? Bahwa perdamaian tidak akan datang dari mengagungkan satu budaya di atas yang lain, atau dengan mengeneralisasi manusia berdasarkan asal-usulnya. Perdamaian sejati hadir ketika kita berhenti mengotakkan manusia dan mulai melihat mereka sebagai individu yang unik, penuh potensi, dan bisa menjadi agen kebaikan, di mana pun mereka berada.
Maka tugas kita, sebagai warga Tasikmalaya yang pernah menengok dunia, bukan untuk meniru Barat secara membabi buta, bukan pula untuk menolak segala hal yang datang dari luar. Tapi untuk bersikap kritis, selektif, dan bijak: mengambil nilai-nilai positif dari mana pun, tanpa kehilangan akar kita sendiri.
Perjalanan saya ke Eropa bukanlah bentuk pengasingan dari jati diri lokal, melainkan bentuk pencarian yang justru menegaskan siapa saya. Saya percaya, dengan cara berpikir yang terbuka, non-essentialist, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal, kita bisa membangun dunia yang lebih damai, dimulai dari Tasikmalaya, dari keluarga kita, dari percakapan harian kita.
Dan di situlah letak harapan: bahwa peradaban tidak lagi bersumber dari satu kutub, tapi dari setiap manusia yang memilih untuk berpikir jernih, bertindak adil, dan hidup dalam semangat saling memahami. (Arini Nurul Hidayati)
Penulis merupakan Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unsil, saat ini sedang menempuh studi doktoral di University of Galway, Irlandia