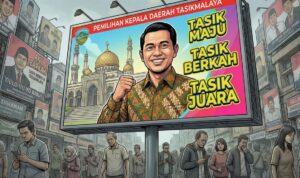RADAR TASIKMALAYA – Gelombang demonstrasi yang melanda berbagai daerah akhir-akhir ini memperlihatkan kekecewaan rakyat yang begitu dalam terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Slogan-slogan bernada sinis, hujatan terhadap anggota dewan, hingga tuntutan ekstrem agar DPR dibubarkan bergema.
Kemarahan rakyat ini lahir dari akumulasi berbagai persoalan baik kebijakan kontroversial yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat, skandal korupsi yang terus menjerat para penguasa, hingga gaya hidup mewah segelintir wakil rakyat yang kontras dengan penderitaan publik.
Namun pertanyaannya, apakah wajar adanya tuntutan membubarkan DPR? Apakah secara konstitusional hal itu mungkin dilakukan, dan apa konsekuensinya jika hal tersebut dijalankan?
Teori trias politica yang digagas Montesquieu menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga cabang ini bukan hanya untuk membagi kewenangan, melainkan juga untuk menciptakan keseimbangan agar tidak ada kekuasaan yang absolut.
Di Indonesia, Presiden/Kepala Daerah menjalankan fungsi eksekutif, DPR/DPD/DPRD memegang fungsi legislasi sekaligus pengawasan, sementara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada di ranah yudikatif.
Dalam kerangka ini, DPR adalah pilar penting bagi negara. DPR bukan sekadar lembaga pembuat undang-undang, tetapi juga wadah representasi rakyat yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Tanpa kehadiran DPR, fungsi pengawasan akan lumpuh. Presiden akan memegang kendali penuh atas negara, dari pembuatan undang-undang hingga penentuan anggaran. Situasi demikian justru mengkhianati prinsip checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi.
Konstitusi kita juga menutup rapat-rapat ruang pembubaran DPR. Pasal 7C UUD UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie pernah menegaskan bahwa pasal tersebut adalah “benteng konstitusional” untuk mencegah kembalinya praktik kekuasaan eksekutif yang absolut.
Menurut Jimly, “kalau DPR bisa dibubarkan, maka tidak ada lagi yang mengontrol Presiden. Itu sama saja kita kembali ke sistem otoriter.” Hal ini yang harus diingat, kejadian 1998 terjadi bukan karena rakyat membubarkan DPR, melainkan karena rakyat menolak kekuasaan absolut yang lahir dari lemahnya perimbangan politik. Jangan sampai sejarah itu diabaikan.
Kekecewaan rakyat memang memiliki dasar. Kasus korupsi berjamaah di Senayan semakin merusak citra lembaga legislatif. Tidak sedikit pula kebijakan yang disahkan tanpa melibatkan partisipasi rakyat secara berarti, apalagi opini-opini oknum DPR yang sama sekali tidak pro rakyat. Semua ini membentuk kesan bahwa DPR bekerja hanya untuk elite politik, bukan untuk masyarakat.
Tetapi menjawab kekecewaan dengan membubarkan DPR ibarat memadamkan api dengan bensin. Negara tanpa parlemen hanya akan membuka jalan bagi otoritarianisme. Meskipun kinerja DPR sering mengecewakan, keberadaannya tetap menjadi pengaman agar negara tidak jatuh dalam jurang otoritarianisme.
Meski demikian, kritik keras terhadap DPR tetap sah dan bahkan penting. Demonstrasi yang menuntut akuntabilitas wakil rakyat adalah ekspresi sehat dalam demokrasi. Desakan masyarakat terhadap buruknya transparansi dalam proses legislasi misalnya yang dianggap berlangsung di balik pintu tertutup, membuat rakyat hanya mengetahui hasil akhirnya tanpa pernah benar-benar dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Padahal, dalam negara demokrasi, rakyat bukan sekadar penonton, melainkan pemegang kedaulatan.
Oleh karena itu, DPR perlu membuka setiap tahap penyusunan undang-undang mulai dari draf awal, pembahasan pasal per pasal, hingga proses pengambilan keputusan secara daring dan dapat diakses publik. Dengan begitu, masyarakat sipil, akademisi, maupun kelompok kepentingan yang terdampak bisa memberikan masukan yang nyata, bukan sekadar formalitas.
Minimnya empati para anggota dewan di Senayan terhadap keadaan aktual ekonomi masyarakat dengan mempertontonkan gaya hidup mewah yang ditunjang dengan penghasilan dan fasilitas yang fantastis seakan menginjak-injak akal sehat rakyat yang telah mengantarkan mereka ke singgasana nyamannya.
Kenaikan penghasilan anggota DPR semakin tidak relevan di tengah pertumbuhan ekonomi yang kian merosot dan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga. Andai saja skema gaji dan tunjangan disusun berdasarkan kinerja (performance-based pay), bukan sekadar jabatan, rasanya kita tidak akan lagi melihat anggota DPR yang jarang hadir atau tidak berkontribusi dalam pekerjaannya mendapat hak penuh atas penghasilan yang diterima.
Selain berdasarkan kinerja, penting juga untuk melakukan penyesuaian penghasilan dan fasilitas anggota DPR yang disesuaikan dengan indikator yang riil seperti kondisi fiskal negara, pendapatan perkapita masyarakat atau rasio utang negara yang tentu saja disampaikan secara transparan kepada publik lewat berbagai kanal pemberitaan baik di digital maupun cetak. Sehingga rasionalitas publik dalam melihat keadaan wakil-wakilnya di Senayan menjadi realistis dan sejalan dengan nasib rakyat yang diwakilinya.
Di sisi lain pola pikir dan mata masyarakat dalam memilih wakilnya di DPR perlu di diarahkan menjadi energi perubahan yang konstruktif. Masyarakat perlu diedukasi dalam mempelajari rekam jejak, pengalaman, dan prestasi calon wakilnya seandainya terpilih di Senayan. Karena bagaimanapun, pemilu adalah instrumen utama untuk “menghukum” wakil rakyat yang tidak amanah dan hanya figur-figur yang lebih kredibel yang layak untuk duduk menjadi anggota DPR.
Hal ini tentu saja perlu didukung dengan reformasi yuridis yang digunakan dalam menyeleksi orang-orang yang akan mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan umum. Standar pendidikan minimal di tingkat sarjana atau pengecualian terhadap mantan terpidana korupsi, pencurian, dan kejahatan seksual misalnya tentu akan menjadi game changer bagi partai politik untuk melakukan rekrutmen anggota dan mencalonkan kader-kadernya sebagai calon.
Dengan kebijakan tersebut, setidaknya memberikan pandangan bahwa anggota DPR hanya diperuntukkan bagi yang memiliki kualitas dan berkeinginan berkontribusi nyata kepada masyarakat dan rakyat tentu akan dihadapkan pada pilihan yang setidaknya “bersih” dari dosa masa lalu yang destruktif.
Harus diakui, demokrasi bukan sistem yang sempurna. Ia penuh cacat, sering mengecewakan, dan kadang membuat rakyat frustrasi. Namun, demokrasi memberikan ruang untuk memperbaiki diri. Dengan adanya DPR, suara rakyat tetap memiliki saluran resmi dalam proses politik. Rakyat boleh kecewa, boleh marah, bahkan boleh turun ke jalan untuk menuntut perubahan.
Tetapi marah yang produktif adalah marah yang diarahkan untuk memperbaiki, bukan menghancurkan. Seruan membubarkan DPR memang terdengar heroik di tengah gelombang demonstrasi, namun dampaknya justru fatal di mana negara kehilangan keseimbangan kekuasaan, rakyat kehilangan wakil resmi, dan demokrasi kehilangan nyawanya. (Sandra Leoni P Yakub)
Penulis merupakan dosen FISIP Unsil