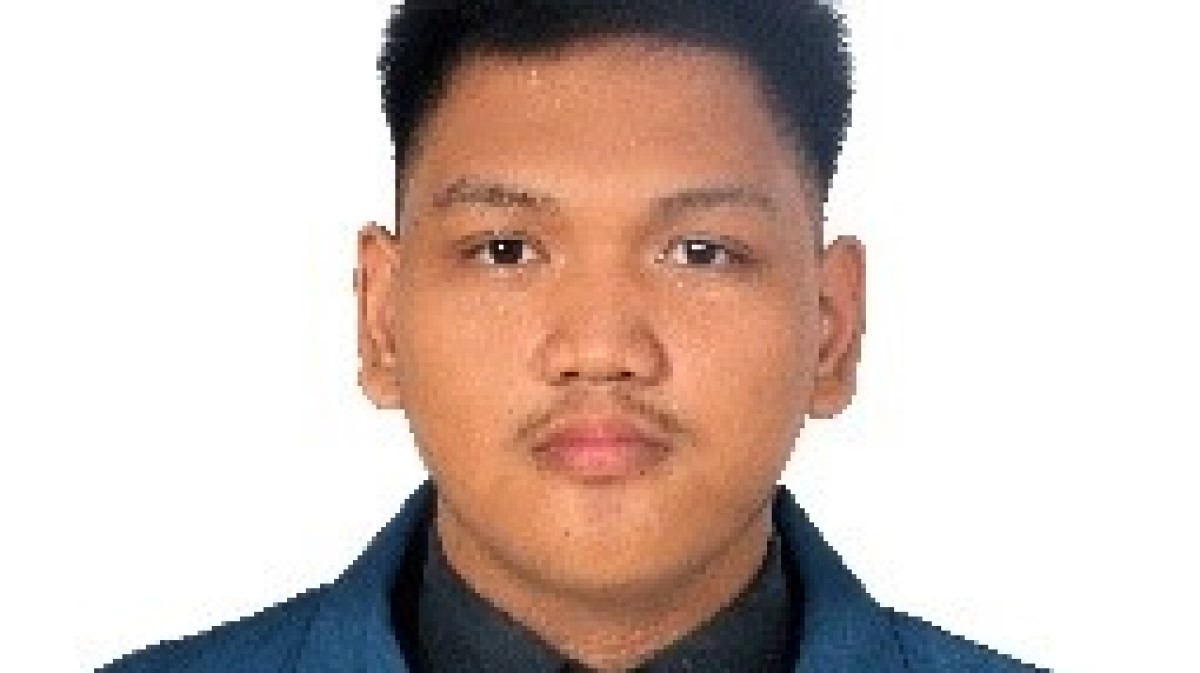RADAR TASIKMALAYA – Feminisme merupakan gerakan sosial, politik, dan ideologi yang mengusahakan hak-hak perempuan dan menetapkan kesetaraan di segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, budaya di antara dua jenis kelamin (Sen, 2016).
Feminisme lahir atas keprihatinan masyarakat khususnya dari kaum perempuan yang memiliki pandangan bahwa kelompok mereka sering mendapatkan penyudutan dan masyarakat luar mempunyai kecenderungan terhadap sudut pandang laki-laki. Orientasi dari gerakan ini adalah untuk menyerukan hak-hak perempuan agar mereka mendapatkan hak yang semestinya, termasuk hak untuk mendapatkan upah yang adil, menghilangkan kesenjangan gender, bahkan hak untuk mengemban jabatan di bidang politik. Feminisme selalu berusaha untuk melindungi kelompok perempuan dari segala penindasan yang berbasis gender.
Gerakan feminisme telah berlangsung sejak lama, gerakan ini lahir pada akhir abad ke- 18 dan mulai berkembang pesat sepanjang abad ke-20 yang dipantik dengan penyuaraan persamaan hak politik bagi perempuan. Seorang sastrawan bernama Mary Wollstonecraft pernah menulis sebuah karya berjudul A Vindication of The Rights of Woman, yang mana tulisan tersebut berisi tentang kritik terhadap Revolusi Prancis yang ia anggap hanya berpihak pada laki-laki dan tidak untuk perempuan.
Maggie Humm dan Rebecca Walker menjelaskan bahwa perjalanan dari feminisme dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama terjadi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, tahap kedua terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an, dan yang terakhir tahap ketiga terjadi pada tahun 1990-an sampai saat ini.
Di Indonesia, gerakan feminisme lahir atas keprihatinan Raden Ajeng Kartini terhadap kondisi perempuan Jawa yang tidak diberikan ruang untuk bergerak oleh pihak Belanda untuk menduduki bangku pendidikan yang setara seperti kaum laki-laki.
R.A. Kartini menggambarkan kondisi perempuan Jawa pada masa tersebut sangat mengenaskan. Mereka terbelenggu oleh sistem tradisi yang berlaku, seperti dilarang sekolah, dipingit, sampai-sampai mereka harus siap dinikahkan dengan laki-laki yang mereka tidak kenali. Oleh karena itu, Kartini berpandangan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan perempuan Indonesia adalah dengan mengupayakan pendidikan yang baik agar dapat mengangkat derajat mereka. Perjuangan Kartini tidak hanya sebatas dalam mengirimkan surat-surat saja, tetapi ia juga membentuk sekolah bagi anak perempuan. Perjuangannya tersebut menginspirasi banyak pihak, hingga akhirnya pada tahun 1907, didirikan Sekolah Kartini di Batavia (Jakarta).
Selanjutnya disusul pembentukan Yayasan Kartini di Den Haag, Belanda, yang kemudian melakukan pelebaran sayap cabang di berbagai kota di Indonesia, seperti Malang, Cirebon, Bogor, Surabaya, Semarang, dan Solo.
Perjuangan perempuan di Indonesia tidak hanya berakhir di sosok Kartini saja, akan tetapi dedikasinya tersebut dilanjutkan oleh seorang tokoh proklamator Indonesia, Sukarno. Hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana seorang Sukarno bisa memiliki pandangan feminisme di pemikirannya. Karena, secara umum pandangan ini biasanya dimiliki oleh perempuan yang dirinya merasa ditindas oleh kaum laki-laki patriarki. Ternyata dibalik itu semua, Sukarno memiliki sosok perempuan yang menjadi dasar dari pemikiran feminismenya, perempuan tersebut adalah Sarinah.
Sarinah merupakan seorang pembantu sukarela di keluarga Sukarno. Sukarno menganggap bahwa gadis pembantu ini memiliki jasa yang besar dalam membesarkannya sebagai seorang penyambung lidah rakyat. Sukarno pernah mengungkapkan dalam otobiografinya yang berjudul, Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia, bahwa “Sarinah adalah bagian dari rumah tangga kami. Tidak Kawin.
Bagi kami, dia adalah seorang anggota keluarga kami. Dia tidur dengan kami, tinggal dengan kami dan memakan apa yang kami makan, akan tetapi dia tidak mendapat gaji sepeser pun (Soekarno, 1947).” Sukarno tidak hanya menganggap seorang Sarinah sebagai pembantu biasa, akan tetapi lebih dari sekadar itu, Sukarno menjadikan Sarinah sebagai guru yang mengenalkan dan mengajarkan tentang arti cinta kasih. Terutama cinta terhadap rakyat kecil atau jelata. Sukarno teringat saat memasak di gubuk kecil dekat rumah orang tuanya bersama Sarinah, ia kerap memberikan wejangan mengenai cinta kasih. “Karno, yang utama kamu harus mencintai ibumu. Akan tetapi kemudian engkau harus mencintai rakyat jelata. Engkau harus mencintai manusia pada umumnya,” ujar Sarinah (Soekarno, 1947). Begitu dekatnya hubungan antara Sukarno dan Sarinah, bahkan saat tidur pun sang proklamator tersebut tidak bisa lepas dari perempuan sederhana tersebut. Kemana pun Sarinah pergi, Sukarno kecil itu selalu membuntutinya.
Sarinah tidak hanya menjadi bagian dari kisah roman kehidupan Sukarno saja, tetapi Sukarno menjadikannya sebagai simbol perjuangan bagi kaum perempuan. Dalam perspektif Sukarno, Sarinah adalah representasi perjuangan perempuan Indonesia, perjuangan yang sering kali terpinggirkan dalam narasi besar kemerdekaan. Ia adalah simbol keberanian, ketulusan, dan pengorbanan tanpa pamrih. Sukarno menggambarkan dedikasi perjuangan Sarinah di bukunya berjudul, Sarinah: Kewadjiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia.
Sukarno juga menegaskan bahwa Sarinahlah yang mengajarkan kepadanya nilai-nilai humanisme, feminisme, dan keadilan sosial yang menjadi inti dari ideologi politik yang mengiringi kepemimpinannya.
Sukarno berpandangan bahwa perempuan memiliki kewajiban dalam perjuangan Indonesia sebagai fondasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Menurutnya, perempuan adalah bagian dari masyarakat, maka persoalan perempuan juga merupakan persoalan masyarakat. Sukarno menyarankan agar perempuan Indonesia mempelajari pergerakan perempuan di barat, lalu memahami dan mengambil contoh-contoh baik yang dapat diterapkan di Indonesia. Jangan sampai perempuan tidak berkontribusi dan merasa dirinya tidak mempunyai hal-hal yang dapat dikembangkan.
Sukarno pernah menuliskan kalimat dalam bukunya berjudul, Sarinah: Kewadjiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia, bahwa “Dan oleh karena soal perempuan adalah soal masyarakat, maka soal perempuan adalah sama tuanya dengan masyarakat; soal perempuan adalah sama tuanya dengan kemanusiaan. Sejak manusia hidup di dalam gua-gua dan rimba-rimba dan belum mengenal rumah, sejak ‘zaman Adam dan Hawa’, kemanusiaan itu pincang, terganggu oleh soal ini.
Manusia zaman sekarang mengenal ‘soal perempuan’, manusia zaman purbakala mengenal ‘soal laki-laki.’ Sekarang kaum perempuan duduk di tingkatan bawah, di zaman purbakala kaum laki-lakilah yang duduk di tingkatan bawah. Sekarang kaum laki-laki yang berkuasa, di zaman purbakala kaum perempuanlah yang berkuasa.
Kemanusiaan, di atas lapangan soal laki-laki perempuan, selalu pincang. Dan kemanusiaan akan terus pincang, selama saf yang satu menindas saf yang lain. Harmoni hanyalah dapat tercapai, kalau tidak ada saf satu di atas saf yang lain, tetapi dua ‘saf’ itu sama derajat, -berjajar- yang satu di sebelah yang lain, yang satu memperkuat kedudukan yang lain (Soekarno, 1947).” Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa Sukarno menjunjung tinggi kesetaraan gender dan sangat menentang dominasi laki-laki yang berlebihan. Menurutnya, harmoni kehidupan dapat dicapai apabila tidak ada yang menganggap kaum laki-laki atau perempuan lebih tinggi atau lebih rendah dari satu sama lainnya.
Pemikiran Sukarno tersebut tidak hanya sebatas ideologi, tetapi dapat diimplementasikan di bidang politik, khususnya keterlibatan perempuan di parlemen Indonesia. Keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting karena dapat menyeimbangkan kekuatan laki-laki yang terlalu mewarnai kehidupan legislatif Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, meskipun masih menemui persoalan dasar. Hal itu diperkuat dengan aturan yang berisi tentang pemberdayaan perempuan di bidang politik yang tercantum dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU); Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol); dan Undang- Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Undang-undang tersebut memberikan petunjuk agar keterlibatan perempuan dalam urusan pemerintahan, baik struktural pusat maupun daerah mencapai kuota 30%. Jika kita lihat dari hasil data rekapitulasi jumlah dan persentase anggota legislatif perempuan di DPR RI periode tahun 2009-2014, hanya terdapat 99 anggota yang berarti hanya memenuhi 17,68%, setengah dari kuota yang disediakan.
Selain di parlemen, sejarah politik Indonesia juga pernah mencatat bahwa terdapat presiden perempuan pertama di Indonesia yaitu Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI keempat. Sebelum mendapatkan mandat menjadi seorang presiden, Megawati telah aktif dalam dunia politik ketika menjadi mahasiswa dengan bergabung ke dalam organisasi GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), sebuah organisasi mahasiswa ekstra kampus yang berlandaskan ideologi nasionalisme dan marhaenisme (Saroh, 2024). Setelah dirasa cukup berpengalaman, akhirnya pada tahun 1986 Megawati mendapatkan tanggung jawab untuk menjadi Wakil Ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Barulah pada tahun 1993, Megawati terpilih menjadi Ketua Umum PDI.
Tidak berselang lama dari terpilihnya Megawati sebagai ketua, pada tahun 1996 terdapat kericuhan pada kongres PDI di Medan yang mengakibatkan terbelahnya PDI menjadi dua kubu, kubu Megawati dan Soerjadi. Peristiwa tersebut biasa dikenal dengan Kudatuli (Kudeta 27 Juli 1996). Pada tahun 1999 bertepatan dengan pemilu, PDI Megawati merubah namanya menjadi PDI Perjuangan dan berhasil memenangkan pemilu. Sidang pada saat itu memutuskan bahwa Gus Dur terpilih menjadi presiden dan Megawati menjadi wakilnya. Pada 23 Juli 2001, MPR RI memutuskan untuk mencabut kekuasaan Gus Dur sebagai presiden dan menetapkan Megawati sebagai presiden pengganti. Kepemimpinan Megawati berlangsung hingga tahun 2004. Perjuangan Megawati tidak hanya berhenti disitu saja, tetapi ia kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2004 dan 2009. Namun, ia gagal dalam pemilihan tersebut.
Pada era kepemimpinan Presiden Megawati, terdapat upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan di legislatif. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-undang tersebut memuat tentang kewajiban partai politik dalam menyediakan kuota 30% bagi kadernya yang berjenis kelamin perempuan dalam pencalonan calon legislatif.
Seiring dengan berjalannya waktu, partisipasi perempuan dalam kehidupan politik Indonesia semakin meningkat, walaupun belum menyentuh angka yang ideal. Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 telah merilis data yang mengungkap jumlah keseluruhan perempuan Indonesia yang menunjukkan angka 49,42% dari total jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Akan tetapi, hanya 20% yang dapat menduduki kursi parlemen Indonesia yang telah diisi oleh perempuan. Meskipun demikian, angka persentase tersebut telah menunjukkan bahwa peran perempuan dalam politik Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dan telah membuktikan bahwa gender tidak menjadi penghalang untuk berkembang.
Selain dalam ranah legislatif, pemerintah juga mengoptimalkan peran perempuan dengan membuat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 10 Tahun 2015 tentang penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa. Dalam peraturan tersebut terdapat kebijakan affirmative action seperti alokasi 30% kursi untuk perempuan dalam rekrutmen BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan 15% pengalokasian anggaran BUMDes untuk kesehatan ibu dan anak.
Pada akhirnya, perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender bukanlah usaha yang dapat dicapai dalam semalam, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kontribusi dan gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa perempuan juga dapat menjadi pilar yang penting dalam perubahan politik dan pembangunan bangsa, sebagaimana telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh seperti Sarinah dan R.A. Kartini. Kini, saatnya kita yang melanjutkan perjuangan mereka dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk turut serta secara aktif di parlemen dan berbagai bidang kehidupan. Sebab, hanya dengan sinergi dan integritas gender, Indonesia dapat mencapai potensi terbaiknya sebagai bangsa yang adil dan sejahtera. (Daniel Trisakusumo)
Penulis merupakan Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Airlangga
Ia meraih Juara 1 lomba esai antar mahasiswa tingkat nasional tahun 2025 yang diselenggarakan UPA Perpustakaan Universitas Siliwangi