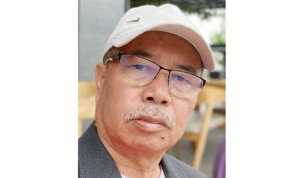RADAR TASIKMALAYA – Gunung Ciremai berdiri tegak sebagai puncak tertinggi Jawa Barat, menjadi penyangga ekologis bagi ribuan warga yang tinggal di sekitarnya. Dari hutan di lerengnya mengalir mata air yang menjadi sumber kehidupan, sementara keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu aset konservasi penting di Indonesia.
Namun di balik keelokannya, Ciremai juga menyimpan potensi panas bumi yang disebut sebagai “emas hijau” masa depan. Pemerintah memandangnya sebagai jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan memenuhi target energi terbarukan. Tetapi, janji energi bersih ini berbenturan dengan kenyataan sosial: penolakan keras masyarakat lokal yang merasa hidup dan ekosistem mereka terancam.
Sejak awal 2010-an, rencana eksplorasi panas bumi di Ciremai terus menuai kontroversi. Pada tahun 2014, perusahaan energi multinasional Chevron pernah mengantongi izin untuk melakukan survei. Namun, proyek tersebut terhambat oleh aksi protes masyarakat. Warga lereng menilai izin dikeluarkan secara tertutup tanpa konsultasi publik.
Mereka bahkan melaporkan kasus ini ke Komnas HAM, menyebut proyek tersebut melanggar hak asasi masyarakat yang bergantung pada tanah dan hutan di Ciremai. Penolakan ini berhasil membuat Chevron mundur, tetapi bukan berarti konflik berhenti. Hingga kini, rencana eksplorasi panas bumi terus dihidupkan pemerintah, sementara resistensi warga tak kunjung reda.
Di lapangan, kekhawatiran masyarakat bukan sekadar spekulasi. Bagi petani, hilangnya lahan dan potensi kerusakan mata air berarti ancaman langsung pada pangan dan penghidupan keluarga. Bagi komunitas adat dan lokal, hilangnya akses hutan sama saja dengan tercerabut dari ruang budaya dan spiritual mereka.
Sementara bagi pelaku ekowisata, kehadiran proyek ekstraktif mengancam keberlangsungan destinasi yang selama ini mereka kelola dengan cara ramah lingkungan. Bukit Ipukan di Kecamatan Cigugur, misalnya, telah tumbuh sebagai destinasi ekowisata berbasis komunitas yang mendatangkan penghasilan sekaligus menjaga kelestarian hutan. Sayangnya, keberhasilan ini kerap dipandang sebelah mata oleh negara, yang lebih sibuk menyiapkan lahan bagi investor.
Peta konflik di kawasan Ipukan memperlihatkan bagaimana aturan zonasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sering kali tumpang tindih dengan praktik kelola warga. Masyarakat yang sudah bertahun-tahun merawat hutan dituding melakukan pelanggaran, sementara investasi berskala besar justru difasilitasi oleh regulasi. Penelitian Maria & Eva (2020) menunjukkan bahwa salah satu akar masalah adalah ketidak jelasan pengakuan hak masyarakat dalam zona pemanfaatan taman nasional. Kondisi ini membuat warga merasa negara lebih berpihak pada modal ketimbang pada rakyatnya sendiri.
Ironisnya, proyek panas bumi yang diklaim sebagai energi hijau justru bisa menimbulkan polarisasi sosial. Studi Sauni, dkk (2019) menunjukkan bahwa ketika proyek energi terbarukan di Indonesia dijalankan tanpa partisipasi penuh masyarakat, ia justru menimbulkan resistensi dan konflik berkepanjangan. Fenomena ini juga terlihat di Ciremai: narasi pembangunan hijau tidak cukup untuk meyakinkan warga, sebab mereka lebih melihat risiko konkret yang harus ditanggung sehari-hari. Dengan kata lain, hijau di atas kertas belum tentu hijau di lapangan.
Lantas, bagaimana jalan keluarnya? Pertama, pemerintah perlu menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Masyarakat harus dilibatkan sejak awal, diberi hak untuk menerima atau menolak, bukan sekadar diminta menyetujui keputusan yang sudah jadi. Kedua, mekanisme benefit-sharing yang nyata perlu dirancang: masyarakat lokal harus memperoleh keuntungan ekonomi dan sosial dari proyek, bukan hanya menanggung kerugian.
Ketiga, pengakuan legal terhadap pengelolaan komunitas, seperti KTH di Bukit Ipukan, harus diperkuat agar warga memiliki posisi tawar yang sah. Dan terakhir, perlu inovasi teknologi panas bumi yang minim jejak ekologis, sehingga energi bersih benar-benar tidak mengorbankan konservasi.
Gunung Ciremai adalah simbol dilema besar pembangunan Indonesia: mengejar pertumbuhan energi sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi. Bila pembangunan geothermal terus dipaksakan tanpa mekanisme partisipasi yang adil, ia hanya akan menambah daftar panjang konflik sumber daya alam di negeri ini.
Tetapi bila negara berani mengedepankan masyarakat sebagai mitra sejajar dan menempatkan konservasi sebagai landasan utama, Ciremai bisa menjadi teladan bahwa transisi energi dapat berlangsung inklusif dan berkeadilan. Masa depan energi hijau Indonesia tidak boleh dibangun di atas penderitaan rakyat dan kerusakan alam, melainkan di atas harmoni antara ekonomi, ekologi, dan keadilan sosial. (Naufal Althaaf dan Rahab)
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jenderal Soedirman